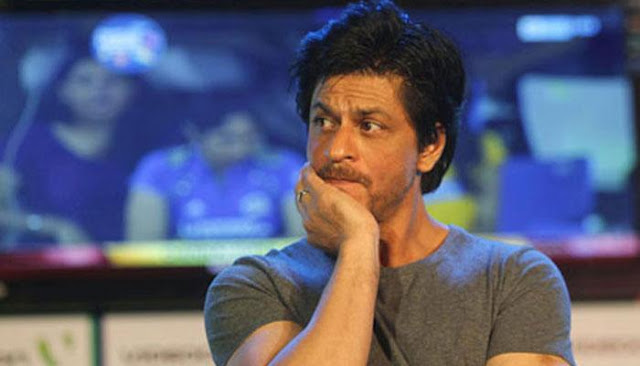
Hampir dua tahun di Semarang, dan rasanya sungguh kesepian. Kota kelahiran yang harusnya jadi titik nyaman saya ini, tiba-tiba berbalik jadi hutan rimba. Sedang Jakarta, yang dulunya bagai kota pesakitan, kini malah tiap hari saya rindukan.
Ini karena, di Jakarta, pemenuhan jiwa mudah saya dapati. Tinggal melipir ke Taman Ismail Marzuki, lalu terbentang di sana aneka pilihan hiburan. Toko buku Jose Rizal? Nonton film Perancis? Mengintip pameran foto? Atau nonton teater saja sekalian di Teater Kecil. Kalaupun sedang tak ada agenda, duduk-duduk di warung makan sambil memaknai semangkok indomie telor kornet dan mengamati dedek-dedek cantik latihan menari, juga sudah menenangkan.
Ini pasti berlebihan, tapi TIM melakukan itu ke saya: menggenapi kebutuhan akan rasa nyaman. Kala itu, saya punya Gloria, sahabat terbaik saya, yang aktif mengajak saya main ke TIM, atau diskusi buku dan sejenisnya di sekitaran Ibukota.
TIM menyuguhkan aneka ilham buat saya, termasuk suatu hari saat ada demo kecil di depan TIM. Saya dan Gloria berhenti, menyimak orang berorasi. Seorang lelaki berjenggot, bersorban, berdiri dan berteriak. Saya lupa apa yang doi gaungkan; karena memang tak penting buat saya. Lalu lelaki itu duduk, gantian orator lain bicara. Saat itulah, saya melihat seorang perempuan berbaju ketat, melenggok lewat di depan si lelaki bersorban. Mata lelaki itu seketika teralih, mengamati tubuh si perempuan. Tatapannya turun, dari rambut, pinggang, ke pantat. Agak lama si lelaki bersorban ini memandang tubuh bagian belakang si perempuan itu. Dan tidak kuasa, saya berbisik, “Podo wae ternyata. Arep dianggoni sorban gamis koyok opo, lanang ki yo tetep lanang, yo?”
TIM dan segala keunikannya menyihir saya. Yang saya sesalkan hingga kini adalah: belum sempat singgah ke Kenduri Cinta-nya Cak Nun. Ah, tidak hanya TIM, tapi juga Perpustakaan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Gloria membawa saya ke sana saat kami menyelesaikan skripsi. Sungguh, surga dunia, karena pilihan bacaan terbentang luas di sana, tentu mayoritas bertema keagamaan. Ada juga, forum diskusi, pemutaran film, serta Sayembara Ahmad Wahib yang digelar Forum Muda Paramadina. Bedah buku. Diskusi buku. Kami datangi semua. Tujuannya: memperkaya jiwa. Menambah wawasan.
Begitu pulang ke Semarang, otomatis saya kehilangan Gloria karena doi bekerja di Jakarta. Sempat ada Endin, sahabat plesiran saya. Kami main ke pameran buku dan acara kesenian. Sekarang Endin juga merantau. Dan di sinilah saya menghadapi kesendirian: ke mana cari pemenuhan jiwa seperti di Jakarta? TBRS? Kota Lama? Dan yang lebih krusial: dengan siapa?
Barangkali saya tak pernah berkomunitas, karena itu-itu saja teman baca dan tulis saya: Gloria, Endin. Kalau teman ngobrol dan sharing sih ada Muy atau Bojo, tapi keduanya juga sibuk dengan kehidupan masing-masing, dan jarang saya ajak ngobrol soal buku dan tulisan, memang. Lebih seringnya sharing yang "aneh-aneh", yang nggak saya sharing-kan ke Gloria atau Endin, wkwk.
Saat semuanya kini jauh, kegelisahan akhirnya jadi derita saya sendiri. Saya butuh teman. Suatu malam, keputusan itu datang, “Mungkin saya harus berkomunitas, biar tetap waras.”
Pasalnya, meski adik-adik saya gemar membaca, mereka tak pernah seratus persen tertarik saat diajak bicara soal Cantik itu Luka, atau Pasung Jiwa. Adik Pertama lebih suka buku puisi Kahlil Gibran. Adik Kedua lebih suka buku bertema psikologi. Ketidaknyambungan obrolan ini membawa saya kembali sendiri. Berbagi bacaan dan tulisan di media sosial tentu membantu, tapi jelas, lebih enak bisa ngobrol langsung, bukan?
Di situ, saya jadi makin menghargai makna kehadiran seorang teman, partner, juga komunitas, yang mampu jadi teman belajar. Bagi saya, secara sederhana, komunitas adalah wadah untuk menjaga kewarasan, dengan berbagi, diskusi, dan dalam konteks ini maka juga: berliterasi, mengabadikan diri lewat tulisan, meski saya hanya mampu bikin curhatan macam ini. Komunitas adalah wadah pemuasan diri, tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang mencari rumah.
Saya pikir, kesendirian ini bisa berlalu dengan mudah. Toh, saya juga senang sendiri; minim gangguan, lebih mudah fokus. Tapi, tetap saja, manusia butuh teman.
Maunya sih ama kamu. Iya, kamu...
#plak
Akhirnya, lahirlah Katadara, sebagai buah keresahan, meski belum maksimal betul karena yang bersangkutan lagi pada sibuk: bekerja sebagai dokter, dan menyelesaikan studi S2.
Akhirnya, lagi-lagi, saya sendiri....
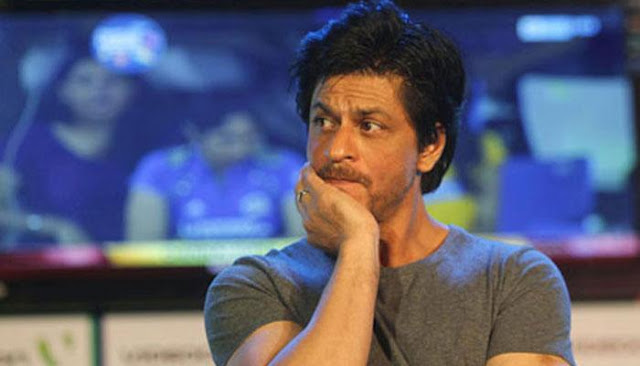
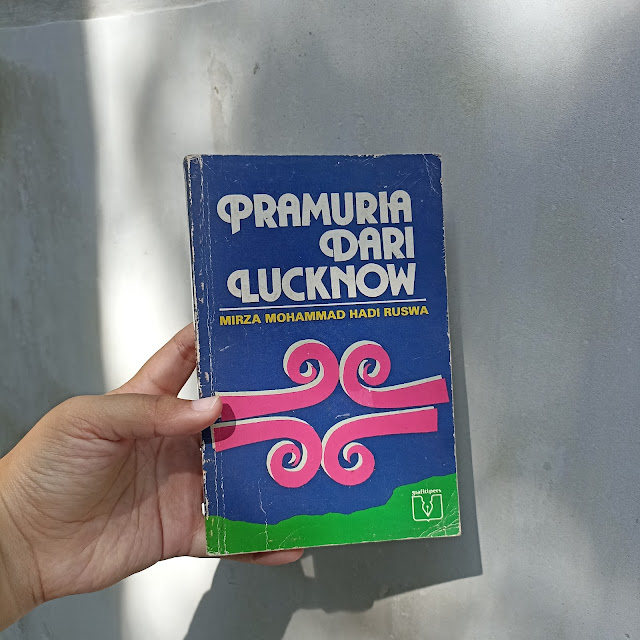
Komentar
Posting Komentar