We truly can’t judge the book by it’s cover.
No, it isn’t only the cover, but also the kata pengantar or
pendahuluan.
And... hey, you also can’t judge it by reading them only
page to page.
You can’t even judge it though you finish the book, because
you can be so subjective.
Perspective does exist, right.
Seperti halnya kamu mengira tulisan ini bakal keren, bakal
membawamu menembus garis batas cakrawala terluar dari alam khayalmu. Begitu?
Ha ha ha.
*
Yang jelas, intinya, gue abis kena tampar. Ditampar oleh
kenyataan bahwa mbak-mbak kemayu itu ternyata sesuatu.
*
Aku pikir dia mbak-mbak kekinian yang "kosong". Meja kamar
kosnya dipenuhi alat rias. Aneka rupa cream
tanpa label. Tau kan, khas cream wajah
ala dokter-dokter gitu. Then, di rak sepatunya penuh heels-heels. Kutebak, harganya tak semahal bentuknya. Mungkin beli
di Ramayana, bagus rupa, bagus harga. Kualitas? Entah. Hampir dua bulan kos di
sini, aku tak melihatnya memakai satu pun heels
itu. Ya ke kantor pakai sepatu itu saja. Di kos pakai sandal. Gitu terus. Njur dipakainya kapan? Halah. Bukan
urusanku.
Bukan urusanku juga dia perempun baik-baik atau bukan. Yang
jelas, dia merokok.
Itu juga yang disampaikan Mbak Umi, istri Mas Catur, penjaga
kosku. “Ya di sini memang ada sekian orang merokok. Kebetulan Mbak diapit sama
mereka...”
“Siapa aja yang ngerokok, Mbak?”
“Hmm, di samping kanan kamar Mbak, samping kiri, depan, sama
samping kanan depan kamar Mbak. Dua diantaranya pakai jilbab, Mbak.”
“..... wow.”
Lengkap. Asap rokok itu bakal mengepul jadi satu di depan
kamarku. Jadi ingat, kalau aku meninggal mendadak di kosan, tolong paru-paruku
diperiksa. Siapa tahu aku korban perokok pasif?
Awalnya kupikir mereka perempuan-perempuan mengesalkan. Tapi
rupanya cukup santun juga. Waktu mereka ingin merokok di
depan-kamar-Mbak-Mbak-kemayu, yang adalah persissssss di depan kamarku, mereka
mengetuk pintu kamarku. Minta izin. Tapi waktu itu aku sudah pulas, dan lupa
mematikan lampu kamar. Jadi mereka merokok saja gitu. Dengan tanpa sadar, aku
menghirup asap demi asap rokoknya.
Syahdu.
Saya bukan benci perokok. Yah elah, saya dikelilingi mereka.
Yang sampai nyimeng juga ada. Cuma, ternyata, nggak enak lho ngisap asap rokok
itu.
*
Mbak kemayu ini rupanya sudah dianggap “hitam” oleh penjaga
kos. Dia pernah menghasut teman-teman kos untuk demo, meminta agar diperbolehkan
merokok di lorong kos. Tidak hanya di balkon. Bahkan mereka memfitnah penjaga
kos, sampai di empunya kos marah dan menganggap penjaga kos nggak bisa sabar
mengurus anak-anak kos.
*
Mbak kemayu ini juga kelewatan. Wajahnya.. oke. Jujur.
Suaranya... bagus, jujur. Tapi aku paling tidak bisa melihatnya bersuara
super-sok-imut. Melengking manja. Geli dengarnya.
Pernah, suatu ketika, Nadia cerita kalau Mbak kemayu ini
mengaku “lagi pemotretan” saat bicara ditelepon. Kebetulan dia telepon di
balkon, Nadia juga sedang di situ. Mau tidak mau dia dengar. Dan, lha si Mbak kan lagi dudukan di balkon? Kok
bisa lagi pemotretan?
Begitulah.
Pokoknya buat saya, Mbak kemayu ini nol besar. Kosong.
Ditambah gaya bicaranya yang genit, jelas sudah. Dia bukan apa-apa. Cuma perempuan
yang pingin dianggap oke saja.
*
Sampai, suatu ketika, saya mendengarnya menyanyi, di kamar
mandi.
Sebuah lagu. Lalu, sebuah lagu lagi. Lalu, sebuah lagu lagi.
Lalu dia ulangi lagi.
Suara indahnya, menghantam telingaku. Aku kaget.
Dan kuuu harap,
menjadi bagianmu
Kubisa gila tak
berharap
Dan kuuu harap,
menjadi harapanmu
Kuuu bisaa gilaaa.
Sesimpel itu. Si Mbak kemayu, Mbak kosong itu, mendadak
mengajariku sesuatu. Mendadak berubah. Dia bukan perempuan kosong.
Karena, perempuan kosong tak akan menikmati lagu-lagu Sore.
Hingga hapal. Hingga menyanyikannya terus-menerus. Hanya mereka yang kuat iman
yang bakal melakukannya. Bagiku, menggemari Raisa itu super biasa saja.
Menggemari Tulus, oke lah. Efek Rumah Kaca? Wow. Payung Teduh? Wah, boljug.
Sore?
Bagiku, orang bisa dinilai lewat musik yang dia dengarkan,
sukai, jiwai, maknai. Menggemari Sore adalah sefantastis menggemari Frau.
Float. White Shoes. Menurutku, mereka keren. Jadi, pendengarnya adalah juga
orang-orang “keren”. Karena Mbak kemayu itu fasih menyanyikan Sore, maka, dia
bukan perempuan kosong. Setidaknya sudah terisi setengah.
Maka dengan begini, aku sudah dua kali menilai buku dari
bungkusnya saja. Seenak rasa.
Maka, pahamilah, ini sesusah tidak mencontek saat ujian,
sementara mencontek saat ujian itu bukan sesuatu yang disarankan. Ini sesusah
tidak memakan mentah-mentah headline-headline
media online, sementara kita
berwatak mudah tersulut begitu baca headline
tertentu. Ini sesusah menahan godaan untuk scroll timeline Facebook, ber-mention
ria dengan gebetan, atau kepo Instagram mantan, sementara Bos menunggu
laporan terkini dari kerjaanmu.
Padahal, aku pun sudah melewati lembar pendahuluan dan bab
1. Tapi, “buku” berjudul “Mbak Kemayu” ini rupanya menyimpan kejutan lain. Saya
bersumpah, akan belajar memaklumi dirinya, juga memaklumi saya, yang belum
kunjung bisa menahan diri untuk tidak menilai dari lapis-lapis luar.
*
We truly can’t judge the book by it’s cover.
No, it isn’t only the cover, but also the kata pengantar or
pendahuluan.
And... hey, you also can’t judge it by reading them only
page to page.
You can’t even judge it though you finish the book, because
you can be so subjective.
Perspective does exist.
Seperti halnya kamu mengira tulisan ini bakal keren, bakal
membawamu menembus garis batas cakrawala terluar dari alam khayalmu. Begitu?
Ha ha ha.
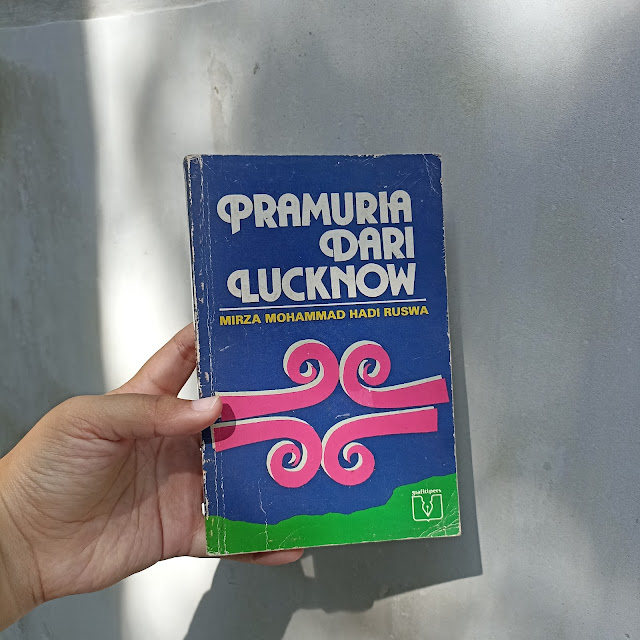
Komentar
Posting Komentar