CATATAN EMPAT TAHUN PERNIKAHAN: "Aku Benar pun Tetap Salah"
Bulan Juni lalu, menjelang ulang tahun pernikahan kami, di tengah momen berbalas chat dengan suami, aku baru menyadari sesuatu. "YANG! Kita tuh udah empat tahun nikah, lho. Kirain baru tiga tahun." Aku punya patokan khusus untuk memudahkan menghitung pernikahan kami. Tahun pertama menikah itu memorable karena aku harus operasi pengangkatan miom. Yes, halo sobat SC. Sayatan lukaku tentu enggak ada apa-apanya dibanding kalian, tapi sama-sama berbekas dan sering gatel atau nyeri kalau kecapekan. Tos. Sisanya maka tinggal ditambah usia Rawi, yang lahir di tahun kedua pernikahan kami. Ada yang bilang, pernikahan itu yang penting komunikasi. Yes, penting banget memang. Seratus persen aktivitas pernikahan itu sangat terkait dengan komunikasi. Kran kamar mandi rusak, ngomong. Perlu belanja ini itu, ngomong. Pengen gantian momong anak, ngomong. Semua kesepakatan dalam rumah tangga, tentang ke mana anak akan disekolahkan, tentang bagaimana mendidik anak sesuai usianya, tentang mainan...

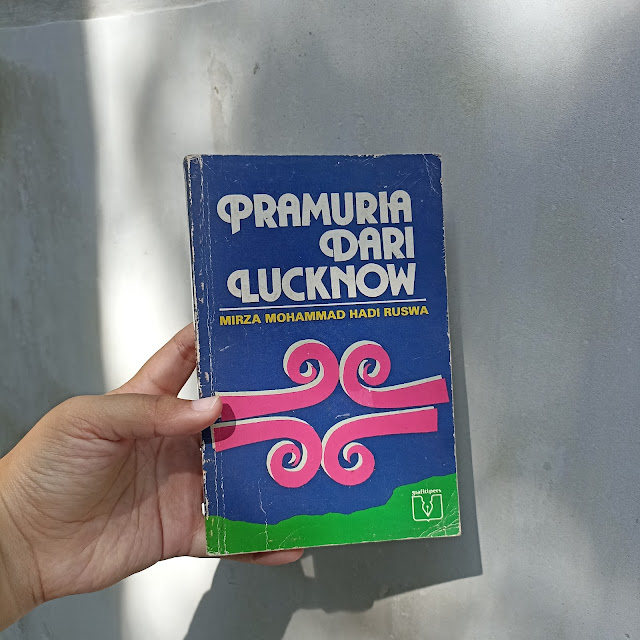
Komentar
Posting Komentar